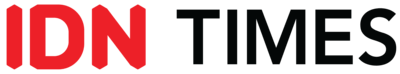Permendikbud dan Lelucon Seksual di Kampus, Harus Bagaimana?
 ilustrasi orang tertawa (pixabay.com/Elena Buzmakova)
ilustrasi orang tertawa (pixabay.com/Elena Buzmakova)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gaung jargon humoris sekaligus filsuf humor Indonesia, Arwah Setiawan, yang dikumandangkan 44 tahun silam akhirnya sampai juga ke telinga pemerintah.
Pada 26 Juli 1977, Arwah “berdemo” sendirian di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam ceramah kebudayaannya, ia membawakan kredo bahwa “humor itu serius” dan mengkritisi banyak hal.
Ia menyoroti rendahnya penghargaan terhadap humor sebagai produk budaya sekaligus kepada profesi pelawak serta timpangnya karya para ilmuwan Tanah Air dibandingkan ilmuwan luar negeri dari segi kajian humor. Arwah juga menyinggung cara kita dalam memanfaatkan humor yang masih sangat terbatas.
Kata Arwah, humor kita--yang lazim dirangkai menjadi format lelucon (joke)--masih sering berkutat pada hal-hal yang “dangkal-dangkal” saja. Semacam mengolok kekurangan fisik orang lain dan seputaran toilet atau ranjang.
Padahal, ketika kita berwawasan luas plus menyadari cara memanfaatkan humor, kita bisa “menggelitik” psikis orang lain melalui banyak topik lelucon.
Nah, terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, pelontar lelucon innuendo (sindiran) sudah bisa dikenakan sanksi.
Lelucon cabul, kini secara spesifik serta eksplisit diatur dalam beleid tersebut, tepatnya pada pasal 5 sebagai produk yang haram beredar karena termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual.
Detailnya pasal 5 ayat 2 adalah bahwa kekerasan seksual yang dilarang meliputi: (c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; serta (e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.
Hemat saya, diakuinya lelucon seksual sebagai suatu bentuk kekerasan merupakan langkah yang tidak asal. Justru dasarnya ilmiah, terutama ketika dilihat dari pendekatan psikoanalisis.
Gershon Legman dalam Rationale of the Dirty Joke: An Analysis of Sexual Humor (1968), mengungkap bahwa lelucon cabul bisa menjadi bentuk pemerkosaan secara verbal (verbal rape). Argumentasi itu mengacu pemikiran Sigmund Freud dari Jokes and Their Relation to the Unconscious.
Freud bilang, pelontar lelucon seksual lazimnya mendapat kesenangan ketika para pendengar lelucon tersebut membayangkan kecabulan di dalam kepala mereka masing-masing.
Nah, apabila audiens lelucon cabul itu adalah pihak atau kelompok yang lebih lemah dalam skema relasi kuasa, atau mau tidak mau terekspos oleh penggambaran cabul tersebut, di sinilah lelucon menjadi alat untuk melakukan kekerasan seksual.
Baca Juga: Buku Humor Pandemik COVID-19 Komedian Kelik Pelipur Lara, Lucu Abis!
Langkah ke depan
Humor bisa dibilang salah satu insting khasnya manusia. Mau dilarang seperti apa juga, manusia tetap akan memproduksi dan menikmatinya.
Justru, keran humor makin terbuka lebar ketika kita sedang berada dalam ketidakberdayaan untuk melawan atau mengubah keadaan. Contoh ekstremnya adalah saat Nazi sedang berkuasa dan tak ragu menunjukkan kebengisannya. Orang-orang justru tidak berhenti mengedarkan lelucon yang mengkritik rezim, sekalipun pelontarnya dibayangi hukuman mati.
Bak membaca kisah dongeng yang happy ending, humor sudah dari sononya menjadi medium bagi manusia untuk kabur dari realita pelik yang dihadapinya.
Di sisi lain, perguruan tinggi layaknya tidak anti dengan humor, karena pelbagai riset multidisiplin telah membuktikan ragam manfaatnya. Humor teruji dapat mempererat hubungan antarmanusia, mempermudah transmisi informasi, termasuk materi belajar, hingga memantik kreativitas dan meningkatkan resiliensi seseorang.
Walau begitu, penggunaannya tetap perlu dimanajemen agar dapat menghasilkan hasil-hasil yang dikehendaki.
Untuk merespons Permendikbud tersebut, perguruan tinggi perlu berbuat dua hal dalam waktu dekat. Pertama, mendorong dan mempromosikan seluas mungkin penggunaan humor secara sadar di kalangan warga kampus.
Sama halnya dengan hasil dari mengontrol insting kita yang lain, berhumor yang didasari oleh kesadaran bakal mendatangkan lebih banyak faedah daripada kemudaratannya. Yang saya dapatkan selama belajar di Humor Academy yang digagas Association for Applied and Therapeutic Humor (AATH), indikator humor yang dilahirkan secara sadar itu sesederhana ketika humor menjadi alat untuk tertawa bersama orang lain, bukan mentertawakan orang lain (laughing with, not laughing at others).
Kedua, Kemendikbud dan perguruan tinggi perlu memasyarakatkan aturan itu secara masif. Sebab, sia-sia sekali jika civitas academica masih banyak yang tidak tahu jika mereka telah diikat sekaligus dilindungi oleh peraturan yang beres diteken Nadiem Makariem tersebut. Apalagi, upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual berbentuk lelucon tersebut sudah lebih konkret dibandingkan apa yang dibuat instansi lain, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan.
Kendatipun Kemenaker punya Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, sayang sekali sosialisasinya belum luas. Alhasil, sejumlah instansi mengimplementasikannya secara sporadis atau malah abai dalam mengontrol peredaran lelucon seksual di lingkungannya.
Andaikan Arwah Setiawan masih berada di antara kita, ia mungkin akan sedikit memodifikasi kredonya agar kasus macam dugaan pelecehan seksual di tubuh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dilabeli sebagai “candaan belaka” tak terulang. Sebab ternyata, “humor itu serius, tapi humor yang kelewatan dampaknya lebih serius.”
Artikel ini merupakan tulisan opini yang ditulis oleh Peneliti Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3), Ulwan Fakhri.
Baca Juga: Fakta Sejarah Penetapan Tanggal Lahir Gus Dur Jadi Hari Humor Nasional