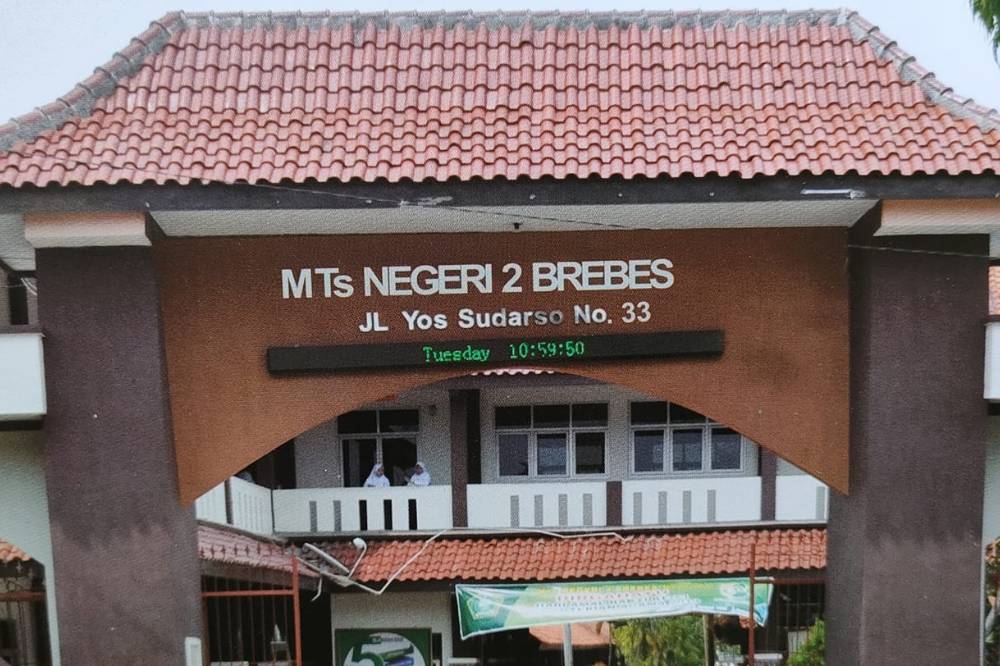Apa Kabar PLTSa? Janji Solusi atau Ilusi Kosong Proyek Mahal

- Sampah plastik di Indonesia mencapai 34,2 juta ton pada tahun 2024, dengan 19,74 persen atau sekitar 6,75 juta ton merupakan sampah plastik.
- Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi hambatan utama, dimana hanya sekitar 18 persen dari total sampah yang berhasil dikelola secara layak.
- Proyek pembangunan PLTSa di Indonesia terkendala oleh berbagai faktor seperti perizinan, pembiayaan, dukungan pemerintah daerah, dan teknis implementasi proyek.
Sampah plastik masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling serius di Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pengelolaan limbah plastik di Tanah Air masih jauh dari optimal. Permasalahan ini kian kompleks dan mendesak untuk segera diatasi.
Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, pada tahun 2024 sebanyak 34,2 juta ton sampah dihasilkan dari 317 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19,74 persen atau sekitar 6,75 juta ton merupakan sampah plastik. Angka itu menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, mengingat pada 2010 jumlah sampah plastik tercatat sebesar 11 persen dan naik menjadi 19,26 persen pada 2023.
Peningkatan volume sampah plastik tidak lepas dari gaya hidup masyarakat yang sangat bergantung pada plastik sekali pakai—seperti kemasan makanan, minuman, hingga kebutuhan rumah tangga harian. Sayang, masih rendahnya kesadaran publik dalam memilah dan mengelola sampah, ditambah dengan minimnya kegiatan daur ulang, membuat masalah tersebut makin pelik. Praktik membuang sampah sembarangan juga memperparah kondisi lingkungan.
Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi hambatan utama. Mulai dari fasilitas daur ulang yang belum merata serta sistem pengolahan yang belum terintegrasi menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Lebih buruk lagi, sebagian bocor ke lingkungan terbuka—seperti sungai, laut, atau bahkan dibakar secara sembarangan. Dampaknya sangat nyata: pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga potensi konflik sosial.
Sepanjang tahun 2023, masih dari laporan SIPSN, hanya sekitar 18 persen atau 10 juta ton dari total 56,6 juta ton sampah yang berhasil dikelola secara layak. Sisa limbah masih menumpuk di TPA atau mencemari lingkungan sekitar.
Padahal, berbagai inisiatif telah dilakukan berdasarkan prinsip 3R—Reduce, Reuse, dan Recycle. Contohnya: digitalisasi dokumen untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless), pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, promosi produk isi ulang, pengomposan sampah organik, hingga pengolahan sampah nonorganik menjadi barang bernilai guna.
Beberapa daerah juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Namun, semua itu belum cukup untuk mengimbangi laju pertambahan sampah. Proyeksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan pada 2025, Indonesia diperkirakan menghasilkan 71,3 juta ton sampah per tahun. Situasi tersebut mengancam keberlangsungan TPA yang sudah kelebihan kapasitas dan sejumlah pemerintah daerah kesulitan mencari lahan baru dengan spesifikasi teknis yang ketat.

Kritik datang dari berbagai pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, menilai program pemilahan sampah yang dijalankan pemerintah daerah hanya sebatas pencitraan. Mereka menyebut kebijakan tersebut tidak disertai langkah nyata seperti pembangunan industri pengolahan sampah yang memadai.
Sementara itu, negara lain justru telah menunjukkan langkah konkret. Korea Selatan, khususnya melalui perusahaan daur ulang BECO di Busan, menjadi salah satu contoh sukses pengelolaan sampah secara modern dan terintegrasi. Gedung BECO tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengolahan limbah, tetapi juga dirancang sebagai ruang edukasi publik. Interiornya artistik, bersih, dan dilengkapi dengan karya seni dari bahan daur ulang. Melalui program edukatif interaktif, seperti gim bertema pengelolaan sampah, anak-anak hingga dewasa diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan sejak dini.
Selain itu, fasilitas Saenggok Landfill juga patut menjadi inspirasi. Tempat penimbunan akhir di Busan itu dikelola dengan rapi dan tanpa bau menyengat. Kunci keberhasilannya terletak pada sistem pemilahan sampah yang ketat sebelum masuk ke lokasi akhir. Sampah dipisahkan berdasarkan jenis, diolah menjadi pakan ternak, dibakar di insinerator, atau dimanfaatkan sebagai energi. Abu pembakaran yang tersisa kemudian ditimbun dengan tanah hasil galian konstruksi apartemen, menjadikannya sistem tertutup yang minim limbah.
Sejak beroperasi pada 1996, Saenggok telah melalui dua fase pengembangan dan dirancang untuk menampung lebih dari 20 juta meter kubik sampah hingga 2031. Dengan kapasitas pengolahan sekitar 4.000 ton sampah per hari pada 2024, sistem tersebut terbukti menjadi solusi konkret bagi kota besar seperti Busan.
Indonesia bisa belajar dari model-model tersebut. Pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kampanye atau regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem yang terintegrasi, didukung teknologi, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta sektor swasta.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Amri Nuryadin, menyoroti kelemahan struktural dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa prinsip 3R tidak akan efektif tanpa keberadaan fasilitas pengolahan yang memadai.
“Misalnya sekarang pemilahan sampah. Habis dipilah, mau diapakan? Kan tidak ada industrinya. Itu yang tidak dikedepankan pemerintah,” katanya kepada IDN Times, Sabtu (26/7/2025).
Menurutnya, program pemilahan sampah saat ini cenderung hanya menjadi ajang pencitraan. Setelah dipilah, sampah tetap saja ditumpuk kembali dan berakhir di TPA. Akibatnya, volume sampah terus meningkat tanpa penanganan berarti, yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Salah satu dampaknya adalah tingginya temuan mikroplastik di sungai-sungai Kota Mataram—kondisi yang juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia.
Persoalan makin rumit karena pembangunan TPA baru dihadapkan pada berbagai hambatan teknis dan administratif. Lokasi TPA harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, antara lain: berjarak minimal satu kilometer dari permukiman, memiliki sistem pengolahan limbah leachate, serta desain khusus yang mencegah longsor dan pencemaran air tanah. Kondisi tersebut membuat banyak daerah kesulitan menyediakan lahan baru untuk menampung limbah, sementara TPA lama sudah kelebihan kapasitas.

Dalam situasi yang kian mendesak itu, pemerintah menargetkan 100 persen pengelolaan sampah secara nasional pada tahun 2029. Artinya, seluruh sampah di Indonesia harus diolah secara aman tanpa praktik open dumping atau pembuangan liar. Untuk mendukung misi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeklaim telah mempercepat upaya pengelolaan sampah terpadu.
Salah satu langkah konkret adalah dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 33 lokasi, naik dari target awal yang hanya mencakup 12 kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018. Beleid yang diterbitkan pada 16 April 2018 itu menargetkan pembangunan PLTSa di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Manado, dengan harapan proyek itu rampung dan mulai beroperasi pada 2022.
Ke-12 kota tersebut dipilih karena memiliki volume sampah tinggi, kompleksitas pengelolaan limbah yang besar, serta potensi ekonomi untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan. Proyek itu pun masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah modern yang efisien dan ramah lingkungan.
Namun, realisasi proyek tersebut tidak berjalan mulus. Hingga Juli 2025, hanya dua dari dua belas PLTSa yang benar-benar beroperasi. Yakni PLTSa Benowo di Surabaya dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta. Selebihnya terkendala berbagai faktor, mulai dari perizinan, pembiayaan, dukungan pemerintah daerah, hingga teknis implementasi proyek.
Hasil riset dan investigasi IDN Times mengungkap fakta mencolok tentang efektivitas operasional dua PLTSa tersebut.

Di Surabaya, PLTSa Benowo berhasil mengolah sekitar 1.600 ton sampah per hari dengan produksi energi mencapai 122–166 GWh per tahun—hampir 100 persen efisiensi. Sementara di Surakarta, PLTSa Putri Cempo hanya menerima sekitar 80 ton sampah per hari, menghasilkan listrik sebesar 1–2 MW—jauh dari target 10 MW.
Walaupun secara teknis dianggap berhasil, PLTSa Benowo menyimpan kekhawatiran lain. Walhi Jawa Timur melaporkan kadar partikel debu halus (PM2.5) di sekitar lokasi pembangkit telah melampaui ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hasil pemantauan menunjukkan rata-rata konsentrasi PM2.5 mencapai 26,78 µg/m³—hampir dua kali lipat dari batas aman WHO sebesar 15 µg/m³. Di beberapa titik, kadar tersebut tercatat melebihi 100 µg/m³. Partikel PM10 pun dilaporkan mencapai puncak 150 µg/m³, jauh di atas ambang batas nasional.
Kondisi itu cukup mengkhawatirkan, mengingat partikel PM2.5 diketahui dapat menembus paru-paru hingga ke aliran darah. Paparan jangka panjang terhadap polutan tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya risiko penyakit kronis seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan kematian dini.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Walhi Jawa Timur berencana menyusun policy brief dan mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Jika tidak mendapat tanggapan memadai, mereka mengancam akan menggelar aksi simbolik sebagai bentuk protes. Walhi menekankan pentingnya mitigasi polusi udara yang ditimbulkan oleh PLTSa agar tidak mengorbankan kesehatan masyarakat sekitar.
Di tengah ambisi besar membangun 33 PLTSa hingga 2029, tantangan teknis, sosial, dan ekologis harus dijawab dengan keseriusan, transparansi, dan pengawasan ketat—agar solusi yang ditawarkan tidak menjadi sumber persoalan baru.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (14/5/2025), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan rencana pemerintah untuk menyederhanakan regulasi PLTSa. Ia mengusulkan penyatuan tiga Peraturan Presiden (Perpres) menjadi satu kebijakan terpadu guna mempercepat implementasi dan memperluas cakupan kota dari 12 menjadi 33 lokasi pembangunan PLTSa di seluruh Indonesia.
Namun di tengah langkah ambisius tersebut, muncul kritik dari berbagai pihak. Yayasan Menjaga Pantai Barat (Yamantab), misalnya, menilai PLTSa bukanlah solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. Direktur Yamantab, Damai Mendrofa menegaskan, teknologi seperti PLTSa hanya menyasar sektor hilir, tanpa menyentuh persoalan utama di sektor hulu.
“Persoalan sampah harus diselesaikan dari sumbernya, bukan hanya diolah di akhir. Tanpa penguatan bank sampah, pengelolaan TPS 3R, dan perubahan perilaku masyarakat, PLTSa hanya akan menjadi solusi semu,” kata Damai.
Ia menambahkan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam menekan produksi sampah plastik. Negara seperti Jerman dan Rwanda telah berhasil menerapkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai secara ketat dan konsisten. Sementara itu, Indonesia dinilai masih lemah dalam implementasi, meskipun regulasi sudah tersedia.
Tidak hanya itu, Damai juga mengkritik kurangnya teladan dari pemerintah sendiri. Menurutnya, belum ada keseriusan dari institusi negara dalam menerapkan pengelolaan sampah yang baik di lingkungannya.
“Kalau institusi pemerintah belum berubah, sulit menuntut masyarakat untuk bertindak. Harus ada legitimasi moral,” akunya.
Investasi dalam edukasi dan perubahan perilaku, menurut Damai, jauh lebih penting dan berkelanjutan dibandingkan mengandalkan solusi berbasis teknologi yang berisiko menimbulkan dampak baru, seperti polusi udara.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia mempertanyakan kejelasan teknologi yang akan digunakan dalam proyek PLTSa serta kesiapan sistem pendukung seperti pemilahan sampah.
“Tanpa sistem pemilahan yang matang, PLTSa hanya akan mengolah sampah campuran secara tidak efisien dan justru memperparah kerusakan lingkungan,” ucapnya.
Irfan menyoroti risiko biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Di Bandar Lampung, misalnya, estimasi biaya operasional PLTSa bisa mencapai Rp120 miliar per tahun. Hal itu bisa menjadi beban berat bagi keuangan daerah yang belum tentu berbanding lurus dengan hasilnya.
Ia juga memperingatkan pemerintah agar tidak “latah” mengikuti tren global pembangunan PLTSa tanpa kesiapan teknologi, regulasi, dan infrastruktur yang memadai.
“Kita tidak bisa hanya meniru tanpa adaptasi lokal yang sesuai,” tegasnya.
Dalam konteks teknologi, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menjelaskan, terdapat dua jenis utama dalam pengolahan sampah menjadi energi, yaitu konversi gas metana dan insinerator. Meski demikian, ia mengakui, teknologi insinerator kerap menimbulkan penolakan masyarakat karena dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.
Contohnya terlihat di Desa Temesi, Gianyar, Bali, di mana masyarakat menolak PLTSa karena berpotensi merusak lahan pertanian berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045, terdapat enam titik potensial pembangunan PLTSa di Bali—yakni Sarbagita, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Bangli, dan Klungkung—dengan total kapasitas listrik sekitar 59 MW. Meski tergolong kecil, Fabby percaya teknologi tersebut dapat berkembang jika didukung investasi yang kuat dan tata kelola yang transparan.
“PLTSa tidak bisa dikembangkan oleh individu atau skala kecil. Perlu ada keterlibatan investor besar dan dukungan regulasi yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, ikut menyoroti tantangan finansial dalam pengembangan PLTSa. Baginya, meski ramah lingkungan dan menjadi alternatif pengganti batubara, PLTSa membutuhkan investasi awal yang besar, biaya operasional tinggi, serta belum efisien secara ekonomi.
“Prosesnya rumit karena harus ada pemisahan sampah terlebih dahulu, dan tidak semua jenis sampah bisa diolah. Jadi, biaya tetap tinggi,” kata Fahmy.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Di Jakarta dan Surabaya, misalnya, pemerintah daerah menanggung biaya pemilahan melalui APBD, sementara PLN menangani pembangkit listrik. Kolaborasi semacam itu dianggap efektif dalam menyelesaikan dua persoalan sekaligus: pengelolaan sampah dan penyediaan energi terbarukan.
Fahmy menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Edukasi tentang pemilahan sampah sejak dari sumber harus terus digencarkan agar proses pengolahan menjadi lebih efisien. Selain itu, perguruan tinggi dan lembaga riset harus dilibatkan untuk mengembangkan teknologi PLTSa yang lebih terjangkau dan berdampak luas.
Pembangunan PLTSa di Indonesia berada di persimpangan: antara solusi progresif atau ancaman baru yang menambah beban lingkungan. Jika tidak dirancang dengan matang dan didukung oleh partisipasi masyarakat serta reformasi kebijakan dari hulu ke hilir, proyek tersebut dikhawatirkan hanya menjadi janji kosong yang mahal.