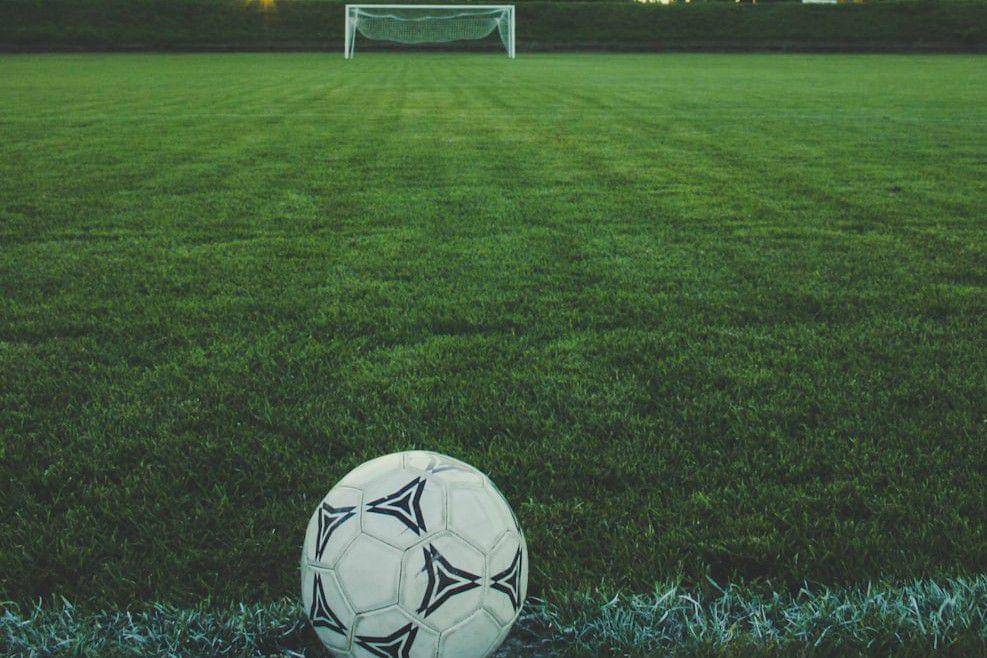[OPINI] Dampak Sosial Ekonomi dari Perubahan Tata Guna Lahan di Kendal

- Kabupaten Kendal mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan lahan terbangun lainnya akibat urbanisasi, pembangunan kawasan industri, dan perubahan kebijakan tata ruang.
- Perubahan tersebut membawa dampak ekonomi seperti potensi penurunan produksi pertanian, pergeseran mata pencaharian, dan kenaikan nilai tanah bagi pemilik lahan.
- Dampak sosial dari alih fungsi lahan termasuk rotasi sosial, perubahan struktur komunitas, pengurangan kapasitas pangan lokal, risiko lingkungan hidup, ketimpangan sosial, dan risiko sosial.
Kabupaten Kendal, yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, memiliki karakteristik agraris dengan persentase lahan pertanian yang cukup besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan lahan terbangun lainnya (infrastruktur/industri) sebagai konsekuensi dari urbanisasi, pembangunan kawasan industri, dan perubahan kebijakan tata ruang. Akibatnya, masyarakat petani dan pengguna lahan tradisional mengalami perubahan struktur sosial dan ekonomi.
Beberapa penelitian dan laporan menguatkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, misalnya, dalam laporannya menyatakan, alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, termasuk permukiman, telah terjadi di wilayah tersebut.
Secara spesifik, penelitian oleh Fitrian Adiyaksa dan Prijono Nugroho Djojomartono (2020) menganalisis alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri antara tahun 2014 hingga 2018. Penelitian yang terbit di Journal of Geospatial Information Science and Engineering (JGISE) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mencatat, Kabupaten Kendal masih memiliki 54,57 persen luas lahan sebagai lahan pertanian dari total luas 1.002,23 km².
Selain itu, studi kasus oleh Afiani Puspita Sari (2016) yang meneliti konversi lahan sawah menjadi perumahan dan industri di Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian telah meluas di jalur Pantura.
Meskipun fokus utama penelitian sering kali pada alih fungsi ke lahan industri atau nonpertanian secara umum, indikasi kuat alih fungsi ke permukiman juga terjadi (seperti kasus di Gemuh). Perubahan tersebut membawa dampak signifikan terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat.
Konsekuensi Sosial Ekonomi

Alih fungsi lahan pertanian menimbulkan sejumlah konsekuensi ekonomi. Pertama, produksi pertanian berpotensi menurun. Ketika lahan sawah berkurang karena dikonversi menjadi permukiman atau lahan terbangun lainnya, hasil komoditas pertanian, seperti padi, juga berpotensi menurun.
Hal itu sejalan dengan publikasi populer yang mengungkap bahwa turunnya produksi pertanian adalah salah satu dampak alih fungsi lahan.
Yang kedua, terjadi pergeseran mata pencaharian. Masyarakat yang sebelumnya bercocok tanam atau sebagai petani mengalami perpindahan pekerjaan ke sektor jasa, konstruksi, atau menjadi pekerja di kawasan permukiman/industri. Contoh di daerah lain seperti Kabupaten Gowa menunjukkan, kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat setelah alih fungsi lahan karena adanya pekerjaan baru.
Terakhir, konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman acapkali mengakibatkan kenaikan nilai tanah bagi pemilik lahan, serta membuka potensi penghasilan melalui penjualan atau pembangunan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Cianjur yang menunjukkan peningkatan nilai lahan akibat alih fungsi sawah ke permukiman.
Selain dampak ekonomi, perubahan tersebut juga memicu dampak sosial. Salah satunya adalah rotasi sosial dan perubahan struktur komunitas. Dengan masuknya pendatang baru, pembangunan permukiman, dan munculnya infrastruktur, struktur sosial petani tradisional dapat terganggu, yang ditandai dengan menurunnya regenerasi petani dan berkurangnya komunitas tani. Hal itu dicatat oleh penelitian Puspita Sari di Kendal mengenai persepsi masyarakat terhadap konversi lahan di Desa Pucangrejo (Electronic Theses and Dissertation (ETD) UGM).
Selanjutnya, alih fungsi lahan produktif menjadi non-pertanian berpotensi mengurangi kapasitas pangan lokal dan menimbulkan tantangan terhadap kualitas lingkungan hidup, misalnya rusaknya irigasi akibat pembangunan di dekat saluran, suatu risiko yang digambarkan Dinas Kabupaten Kendal dalam laman resminya.
Terakhir, perubahan tersebut dapat menciptakan ketimpangan dan risiko sosial. Ketika pemilik lahan menjual kepada pihak pengembang, petani kecil atau buruh tani dapat kehilangan penghasilan tetap dan harus beradaptasi ke sektor baru yang kadang kurang stabil.

Untuk Kabupaten Kendal, perubahan tata guna lahan dari pertanian ke permukiman dan/atau lahan terbangun lainnya dapat ditelaah melalui beberapa faktor utama. Pertama, urbanisasi dan pembangunan kawasan industri (misalnya, kawasan industri di Kendal) mendorong tingginya permintaan lahan terbangun.
Kedua, aksesibilitas lokasi (dekat jalur Pantura dan kota besar) menjadikan lahan pertanian di pinggiran sebagai target konversi. Ketiga, ketika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau izin percepatan pembangunan tidak sepenuhnya mengendalikan alih fungsi lahan produktif, maka laju konversi menjadi cepat.
Terakhir, dampak bagi masyarakat lokal beragam: petani yang kehilangan lahan harus mencari pekerjaan lain, sementara sebagian pemilik lahan mungkin mendapat keuntungan melalui penggantian lahan/penjualan, meskipun ada juga yang kurang siap menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi.

Oleh karena itu, perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Kendal membawa dampak yang beragam terhadap masyarakat. Dari sisi ekonomi, terdapat potensi kenaikan nilai lahan dan diversifikasi pekerjaan.
Namun, di saat yang sama terdapat risiko penurunan produksi pertanian, kehilangan mata pencaharian tradisional, dan perubahan struktur sosial. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan kebijakan yang seimbang antara pembangunan fisik dan pelestarian sektor pertanian, serta pemberdayaan masyarakat terdampak.
Santi Inderawati, ST., MM., Mahasiswa Program Studi (S2) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang juga praktisi pengembang perumahan di Jawa Tengah dan aktif di organisasi DPD Himperra Jateng sebagai Wakil Sekretaris Bidang Perbankan dan CSR.